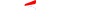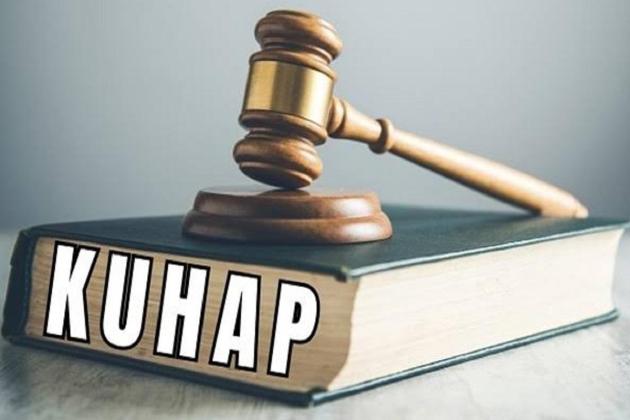11. Fenomena Defisit Anggaran yang Cenderung Berulang
Batas defisit 3% dari PDB dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 sering disalahpahami sebagai target, bukan batas. Data menunjukkan bahwa di luar masa pandemi, APBN hampir selalu dirancang dengan defisit di atas 2%, sebagaimana yang juga terlihat dalam UU Nomor 19 Tahun 2023 untuk APBN 2024. Ini menandakan sulitnya mengerem belanja atau meningkatkan pendapatan saat ekonomi sedang baik, yang justru memperburuk kondisi fiskal jangka panjang. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga menjadi landasan penting dalam mengelola keuangan negara dan defisit ini.
12. Pengukuran Kinerja dari Serapan Anggaran
Budaya ini diperkuat oleh sistem evaluasi. Data dari Kemenkeu menunjukkan, realisasi belanja negara selalu menumpuk di Kuartal IV. Ini menandakan fokus Pemerintah adalah menghabiskan uang, bukan menciptakan dampak sejak awal tahun. Padahal, UU Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Sistem penilaian kinerja PNS sendiri sudah diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Kerangka kerja ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menggarisbawahi pentingnya kinerja aparatur negara.
B. Ciptakan APBN sebagai Mesin Pertumbuhan 8%, Solusi Terukur dan Berani
Solusi-solusi ini sebagian dari praktik terbaik negara lain dan kebutuhan mendesak kita. Semuanya perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah melalui Kemenkeu dan Kementerian terkait dengan persetujuan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pengawasan Komisi XI DPR RI.
1. Kita bisa mengadopsi model Emissions Trading System (ETS) di Uni Eropa yang berhasil menekan emisi dan menghasilkan pendapatan baru. Pada tahun 2023, ETS di Uni Eropa menghasilkan €39,5 miliar (sekitar Rp 680 triliun). Dengan asumsi 10% dari emisi karbon di Indonesia bisa dikenai pajak, potensi pendapatan bisa mencapai puluhan triliun rupiah per tahun. Ini signifikan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendorong investasi hijau yang bisa jadi mesin pertumbuhan baru. Pemerintah perlu bersiap menghadapi resistensi dari industri, namun insentif transisi bisa jadi solusinya. Ini sejalan dengan semangat UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) yang mengatur pajak karbon. Untuk implementasi teknisnya, ada juga Perpres Nomor 98 Tahun 2021.
2. Seperti India dengan sistem Aadhaar atau Estonia dengan X-Road, kita bisa memperkuat integrasi data untuk otoritas pajak, agar bisa melihat semua aliran ekonomi digital secara legal. Langkah ini dapat meningkatkan rasio pajak kita hingga 1-2% dari PDB dalam 5 tahun, atau sekitar Rp 200-400 triliun per tahun. Upaya ini harus sejalan dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan semangat UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) yang mengintegrasikan NIK sebagai NPWP. Tentu saja, langkah ini juga harus sejalan dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi untuk menjaga kerahasiaan data masyarakat.
3. Banyak perusahaan multinasional sudah menggunakan Zero Based Budgeting (ZBB) untuk memangkas pemborosan hingga 20-30%. Pemerintah bisa mengadopsi ini, dimulai dari kementerian yang belanja operasionalnya tinggi. Penghematan dari belanja operasional sebesar Rp 517,6 triliun tahun 2024 bisa mencapai Rp 50-100 triliun, yang bisa dialihkan ke belanja modal produktif. Implementasi ZBB memang memerlukan komitmen politik yang kuat, tapi sangat penting. Pemerintah bisa berkolaborasi dengan Sektor swasta KADIN, APINDO, dan HIPMI untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak ekonomi maksimal. Dasar hukumnya tetap merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Berdasarkan studi Bank Dunia, program bantuan tunai bersyarat seperti di Brazil atau Meksiko bisa mengurangi kemiskinan hingga 25% dan meningkatkan partisipasi sekolah hingga 10-15%. Dengan data yang terintegrasi dari Satu Data Indonesia, bantuan tunai bisa lebih tepat sasaran. Pendekatan baru ini dapat menghemat anggaran subsidi hingga puluhan triliun rupiah dan secara sinergis mendukung digitalisasi pajak serta program bantuan sosial yang lebih efektif, sesuai dengan semangat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Tentu saja, hal ini juga diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
5. Yunani dan Spanyol pernah memangkas belanja operasional saat krisis. Kita bisa melakukannya secara proaktif untuk dialihkan ke dana abadi riset, meniru model Temasek di Singapura. Dana kelolaan Temasek per Maret 2024 mencapai S$403 miliar (sekitar Rp 4.700 triliun), menunjukkan bagaimana dana abadi bisa menjadi sumber pendanaan jangka panjang yang krusial untuk inovasi dan pertumbuhan PDB potensial. Ini sejalan dengan UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mendorong pendanaan riset. Pelaksanaan dana abadi ini juga diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Dana Abadi Penelitian.
6. Memastikan utang produktif, kita bisa mewajibkan analisis Economic Rate of Return (ERR) oleh lembaga independen. Analisis ini memastikan hanya proyek dengan ERR riil di atas social discount rate (sekitar 12-15%) yang lolos. Langkah ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dan akan menekan ICOR. Sinerginya, ini akan membuat utang menjadi investasi riil yang mendatangkan pertumbuhan, bukan sekadar beban. Kerangka kerja ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.08/2021 tentang Pinjaman Luar Negeri dan Hibah.
7. Gunakan Kerangka Anggaran Multi Tahun (MTEF), ini adalah praktik standar di negara maju untuk proyek pertahanan dan infrastruktur. Dengan kerangka ini, Pemerintah dan DPR RI bisa menyepakati anggaran proyek jangka panjang, memberikan kepastian pendanaan, dan meningkatkan efisiensi belanja. MTEF sangat penting untuk proyek-proyek riset yang memerlukan pendanaan stabil selama bertahun-tahun dan akan mengatasi masalah siklus politik yang menghambat proyek jangka panjang, sesuai dengan semangat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penerapan MTEF juga diatur lebih detail dalam PP Nomor 17 Tahun 2017.
8. Bangun National Economic Command Center Berbasis Real Time Data, konsep ini terinspirasi dari delivery unit yang sukses di Inggris. Tujuannya adalah memantau dan mempercepat program prioritas secara terukur, memanfaatkan data dari berbagai kementerian/lembaga sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Tim ini bisa bertindak cepat untuk mengatasi hambatan birokrasi dan memastikan program berjalan sesuai jadwal. Tentu saja, hal ini juga didukung oleh UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
9. Desain Ulang TKDD Jadi Performance Based Grant, model ini sukses diterapkan di Amerika Serikat melalui program Race to the Top, di mana Pemerintah daerah yang berhasil melakukan reformasi mendapat hadiah anggaran tambahan. Model ini bisa diterapkan dengan merevisi UU Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD). Dengan cara ini, daerah akan lebih termotivasi untuk membelanjakan uangnya secara efektif, bukan malah menimbun SiLPA. Pengelolaan keuangan daerah secara umum juga diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.