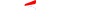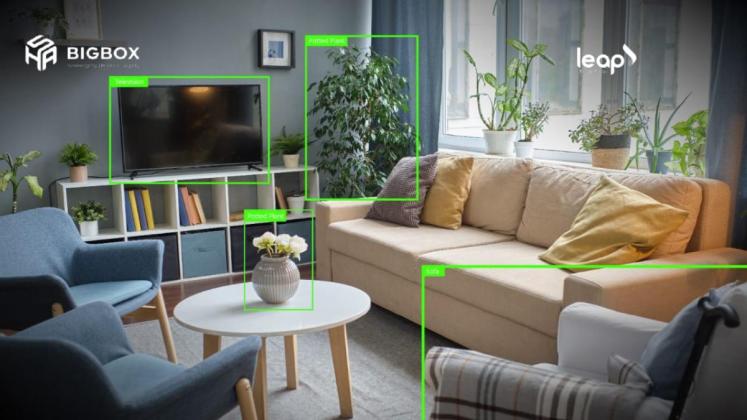Oleh: Amelia Fitriani ( Postgraduate Student in Business & Communication Management LSPR Institute)
“Kita harus bergandengan tangan. Merobohkan batas-batas primordial kesukuan, golongan, ras dan agama.”
Begitu kutipan puisi karya penulis ternama, Ahmad Gaus yang ikut saya bacakan bersama sang penulisnya serta aktivis keberagaman, Mila Muzakkar di acara penutupan workshop Esoterika Fellowship Program yang digelar di Jakarta pada Rabu (23 April 2025).
Fragmen puisi itu menyentuh hati saya karena mewakili ruh besar dari Esoterika itu sendiri yang mendorong semangat kebersamaan sebagai sesama homo sapiens, dengan memaknai lebih dalam agama sebagai warisan kultural milik bersama serta mengamini nilai-nilai spiritual yang universal.
Pada kegiatan tersebut, saya menempatkan diri sebagai seorang pembelajar yang haus akan pengetahuan dan pandangan mengenai nilai-nilai universal dari spiritualitas, yang bisa merobohkan batasan agama. Saya sendiri mengamini ruh dan semangat yang dibawa oleh Esoterika Forum Spiritualitas, sebuah gerakan yang digagas oleh Denny JA.
Di tengah kegiatan kemarin, saya teringat pada pengalaman 10 tahun lalu yang membekas dan mempengaruhi cara pandang saya akan konsep spiritualitas dan agama.
**
Saat itu pertengahan November 2015. Hujan turun rintik-rintik. Tidak ada tanda-tanda kapan berhenti. Ini tidak mengherankan, karena saya tengah berada di Bogotá, Kolombia, salah satu ibu kota tertinggi di dunia. Hujan rintik disertai embusan angin yang menusuk tulang bukanlah sesuatu yang baru di kota, yang terletak pada ketinggian sekitar 2.640 meter di atas permukaan laut ini. November memang masih terhitung musim hujan.
Saya merapikan bufanda, semacam syal rajut tebal, yang melingkari leher untuk menutup semua celah yang bisa disusupi angin. Angin memang kerap hadir menyertai rintik hujan. Napasku tersengal-sengal sesudah berjalan lebih dari satu jam mengelilingi beberapa tempat bersejarah dan museum di kawasan Plaza de Bolívar, yang terletak tepat di jantung Bogota.
Saya sudah berjalan cukup lama menggendong ransel berisi laptop plus buku belajar bahasa Spanyol. Janin kecil berusia dua bulan saat itu ada di rahim saya. Tentu saja ini sangat menguras energi. Saya merasa begitu lelah hingga memutuskan untuk mencari tempat beristirahat. Posisi saya saat itu tidak jauh dari halte bus Transmilenio Museo del Oro. Transmilenio sendiri merupakan sistem transit cepat bus, yang kemudian diadopsi Pemerintah Kota Jakarta menjadi Transjakarta. Ternyata tidak ada tempat yang cukup nyaman untuk berteduh. Sementara saya perlu memulihkan energi agar bisa kembali ke apartemen di dekat Plaza de Las Aguas, yang berjarak kurang dari dua kilometer dari sini.
Saya mengamati suasana sekitar hingga akhirnya melihat Iglesia de San Francisco, gereja Katolik tua yang berdiri pada 1566. Pintu gereja terbuka. Tampak beberapa orang masuk ke sana. Karena merasa begitu lelah, sementara angin nakal makin terasa menusuk tulang, saya memutuskan masuk ke gereja. Saya duduk di barisan belakang di dalam gereja kuno bergaya Spanyol itu. Sejumlah jemaat yang hendak beribadah sore sudah mengambil tempat duduk masing-masing.
Awalnya ada rasa canggung. Bagaimana tidak. Saya seorang perempuan muslim Asia yang saat itu mengenakan jilbab. Dan saya berada di dalam gereja, di tengah-tengah jemaat Katolik Latinos yang hendak melaksanakan ibadah sore. Untungnya, tidak butuh waktu lama untuk merasakan suasana nyaman. Selain berada di ruangan hangat dengan arsitektur sangat cantik, ada lilin-lilin yang membuat ruangan semakin indah temaram.
Di luar dugaan, para jemaat yang hadir tidak memandang saya sebagai “mahkluk” aneh. Sebaliknya, mereka memberikan senyum terbaik dan tatapan lembut dan hangat. Sama sekali tidak ada pandangan sinis atau curiga.
Karena kehangatan ini, saya enggan untuk segera beranjak. Saya terus duduk mengikuti rangkaian ibadah sore. Sejujurnya, saya tidak memahami satu pun ritual yang sedang dijalankan. Khotbah disampaikan dalam bahasa Spanyol. Meski demikian, saya bisa menikmati suasana khidmat yang menyentuh hati. Saya pun terhanyut, terlebih saat memandang cahaya lilin di altar gereja.
Tak terasa, saya masuk ke perenungan diri. Memori saya kembali ke peristiwa beberapa hari sebelumnya, tepatnya tanggal 16 November 2015. Waktu itu saya tengah berjalan menuju kampus Universidad Externado de Colombia, yang terletak di atas bukit, Seorang mahasiswa tiba-tiba datang dari arah belakang. Dengan tatapan sendu, dia bertanya, “Why did you kill innocent people in Paris?” Saya terkejut. Belum hilang keterkejutan itu, laki-laki muda tersebut berlalu masuk ke kampus.