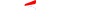JAKARTA, FIN.CO.ID - Berakhirnya masa pandemi Covid-19 tak selamanya membuat tatanan dunia normal. Timbul masalah baru yang tak terduga di sisi perekonomian dunia seperti disrupsi rantai pasok, gangguan suplai, gangguan distribusi barang dan jasa. Akibatnya inflasi di sejumlah negara besar merangkak naik signifikan, cenderung tidak terkendali dan liar.
Sebagai contoh di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Tren inflasi naik terus menerus dan bersifat permanen seiring maraknya konflik dunia. Alhasil gangguan suplai dan produksi semakin luas, krisis energi dan pangan semakin nyata hingga menyebabkan kenaikan inflasi semakin tidak tertahankan. Dalam empat puluh tahun terakhir, inflasi AS dan Eropa memecahkan rekor tertinggi, masing-masing sekitar 9% yoy (Juni 2022) dan 10% yoy (Oktober 2022).
BACA JUGA: Terapkan Strategi Hybrid Bank, Jumlah AgenBRILink Meningkat Pesat
Chief Economist BRI sekaligus Direktur Utama BRI Research Institute, Anton Hendranata menjelaskan, inflasi super tinggi dan tak terkendali telah direspons dengan kenaikan suku bunga acuan secara agresif dan signifikan oleh sebagian bank sentral di dunia, yang dipelopori oleh AS, diikuti Eropa, dan sebagian besar negara-negara berkembang. Konsekuensinya perekonomian global berada dalam risiko yang besar.
“Antibiotik suku bunga dengan dosis tinggi selama lebih dari dua tahun, memang berhasil mematahkan tren kenaikan inflasi, inflasi mulai turun terbatas. Namun, efek buruknya lebih mengkhawatirkan yaitu perekonomian global diambang resesi. Suku bunga tinggi, sangat membebani perekonomian dunia dan dunia usaha, serta menurunkan daya beli masyarakat secara signifikan. Beban bunga pinjaman tinggi menohok sektor riil, sektor perbankan, dan debitur, termasuk individual masyarakat yang sangat bergantung pada kartu kredit”, ucap Anton.
Contoh nyata dari masalah tersebut telah terbukti lewat jatuhnya tiga bank AS yakni Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank, dan First Republic Bank. Hal itu diakibatkan dari kenaikan signifikan suku bunga acuan Bank Sentral AS dari 0,25% menjadi 5%. Selain itu, tingginya suku bunga acuan AS mengakibatkan peningkatan suku bunga kredit perumahan, yang kemudian menyebabkan tingkat pengajuan kredit perumahan rakyat (KPR) turun signifikan.
“Penurunan kinerja sektor properti AS ini harus disikapi dengan hati-hati, karena pertumbuhan private residential fixed investment turun secara signifikan, mendekati kondisi seperti krisis finansial global tahun 2009,” lanjutnya.
Akibat lain yakni kurva imbal hasil (yield) obligasi AS (US Treasury) kini telah mengalami inverted, di mana yield obligasi AS tenor 2 tahun lebih tinggi dari tenor 10 tahun. Belum lagi, berdasarkan penghitungan model Ekonometrika yang dibangun melalui metode Markov Switching Dynamic Model pada Juli 2022 menunjukkan bahwa probabilitas AS mengalami resesi ekonomi tahun 2023 sebesar 80%. Angka probabilitas itu naik signifikan sembilan bulan kemudian (April 2023) menjadi 91%.
BACA JUGA: Bersama Dekranas dan BUMN, BRI Dukung UMKM Naik Kelas dengan Sertifikasi TKDN
“Melihat kondisi AS yang semakin sulit dan bangkrutnya tiga bank di AS. Saya kira kita harus bijak menyikapinya. Kita harus siap dengan kemungkinan terburuk AS akan jatuh terjerembap dalam resesi ekonomi, yang mungkin akan diikuti oleh Eropa, bahkan ada kemungkinan resesinya lebih cepat dibandingkan AS. Pada saat negara maju mengalami resesi, maka akan sulit negara berkembang terhindar dari resesi ekonomi dunia. Apalagi dalam kebijakan moneternya, menaikkan suku bunga acuannya secara signifikan sejalan dengan kenaikan suku bunga acuan AS, dalam rangka menjaga stabilitas nilai mata uangnya terhadap Dollar AS”, lanjut Anton.
Kendati demikian, Anton meyakinkan masyarakat Indonesia agar tidak panik meyikapi kondisi tersebut. Pada nyatanya, Indonesia telah berpengalaman bertahan dalam krisis ekonomi dan finansial global 2008/2009 (GFC 2008/2009). Di saat itu, Indonesia hanya mengalami perlambatan ekonomi namun tidak terseret ke dalam resesi. Perekonomian Indonesia masih bisa tumbuh positif sebesar 4,6% tahun 2009 dari 6% pada 2008.
Padahal di tahun itu, krisis ekonomi yang ditandai kebangkrutan Bank Lehman Brothers daya rusaknya jauh lebih besar dari kolapsnya SVB, Signature Bank, dan First Republic Bank di tahun ini. Lalu indikator persepsi risiko yang diwakili oleh credit default swap (CDS) dari lima bank besar di AS (Bank of America, Citi Group, JP Morgan, Wells Fargo, dan Morgan Stanley) lebih melonjak signifikan pada saat kolapsnya Lehman Brothers. Artinya, kekhawatiran dan ketakutan jatuhnya Lehman Brothers (GFC 2008/09) terbukti kadarnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jatuhnya SVB dan lain-lain.
“Fakta-fakta tersebut, telah membuka nalar sehat kita, bahwa jika AS mengalami resesi tahun 2023, dampak negatifnya kemungkinan besar tidak akan separah krisis ekonomi global 2008/09. Indonesia akan jauh dari episentrum resesi ekonomi global 2023. Fundamental ekonomi Indonesia jauh lebih sehat dan kuat dibandingkan kondisi 15 tahun lalu, pada saat resesi ekonomi global 2008/09,” ucap Anton.
Anton melanjutkan, keyakinan itu diperkuat dengan perhitungan yang telah dibangun oleh BRI pada Juli 2022 yakni menggunakan Markov Switching Dynamic Model. Di sana menunjukkan, jika AS mengalami resesi ekonomi 2023, maka probabilitas Indonesia mengalami resesi ekonomi hanya 2 persen. Angka tersebut sama persis dengan konsensus Bloomberg pada April 2023 ini.
Selanjutnya, Anton menyarankan berbagai pihak untuk memperkuat kekuatan domestik perekonomian Indonesia di antaranya dengan mengoptimalkan konsumsi rumah tangga sebagai motor penggerak utama perekonomian. Di sisi lain, pemerintah harus mampu menjaga daya beli masyarakat level menengah ke bawah dan menggerakkan perekonomian lokal/daerah melalui stimulus fiskal seperti Bantuan Sosial (Bansos), perlinsos, dana desa, dan lain-lain.