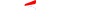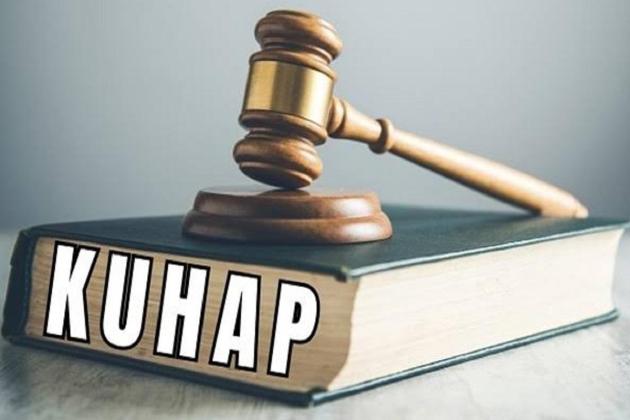Redaksi fin.co.id | EDITORIAL
Rekening Tak Bergerak Dibekukan, Pengangguran Tak Bergerak Dibiarkan: Negara Tak Boleh Memilih-Milih Siapa yang Layak Disentuh
Ketika negara lebih cepat membekukan rekening pasif daripada menyentuh hidup warganya yang tengah berjuang bertahan, kita patut bertanya: ke mana arah empati dan prioritas kebijakan publik hari ini?
Kebijakan terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal pemblokiran rekening tidak aktif selama tiga bulan memicu kegelisahan luas di masyarakat. Bukan karena publik mendukung praktik pencucian uang atau penyalahgunaan rekening, melainkan karena pendekatan kebijakannya yang tiba-tiba, minim sosialisasi, dan menyasar terlalu luas tanpa mempertimbangkan konteks sosial masyarakat Indonesia.
Langkah PPATK memang dilatarbelakangi oleh data: lebih dari 28.000 rekening pasif terindikasi digunakan untuk aktivitas ilegal dengan aliran dana mencurigakan mencapai Rp 4,2 triliun sepanjang 2024. Dari sudut pandang penegakan hukum, langkah ini tentu punya dasar yang kuat. Tapi ketika kebijakan yang semestinya ditujukan pada penjahat digital justru berpotensi mengenai petani, pensiunan, buruh migran, atau mahasiswa yang sekadar tidak aktif bertransaksi, maka negara sedang bermain-main dengan kepercayaan publik.
Apa yang membuat kebijakan ini begitu mengusik?
Satu kata: ketimpangan perhatian. Negara kita tampak begitu tangkas mengurus saldo yang tak bergerak, namun begitu lamban merespons kehidupan warganya yang juga sedang “tak bergerak”—karena kehilangan pekerjaan, karena sistem tak memberi peluang, atau karena sekadar hidup di luar radar ekonomi formal.
Februari 2024, data Badan Pusat Statistik mencatat ada 7,2 juta pengangguran terbuka di Indonesia. Jika ditambah pekerja informal dan mereka yang bekerja tak sesuai kompetensi, angkanya bisa menyentuh 15 juta jiwa. Tapi, sejauh ini belum ada kebijakan secepat dan setegas pemblokiran rekening untuk menyapa mereka. Negara belum secara sistemik bertanya: "Mengapa kamu menganggur? Apa yang bisa kami bantu?"
Negara justru memilih menyasar diamnya rekening. Bukan diamnya manusia.
Ini menjadi ironi besar. Rekening pasif diblokir dalam waktu tiga bulan, sementara pengangguran bisa dibiarkan bertahun-tahun. Tak ada notifikasi. Tak ada edukasi. Tak ada sistem respons cepat seperti yang diterapkan di negara-negara dengan sistem jaminan sosial maju seperti Jerman, Australia, atau Singapura.
Lebih menyedihkan lagi, ketika warga mempertanyakan kebijakan ini, yang mereka dapat bukan jawaban meyakinkan, melainkan asumsi: “Jika rekeningmu diam, bisa jadi kamu sedang menyembunyikan kejahatan.” Ini bukan hanya bentuk ketidakadilan prosedural, tapi juga bentuk pengabaian terhadap realitas sosial masyarakat yang tidak semuanya hidup dengan pola konsumsi dan transaksi digital harian.
Apakah semua warga Indonesia setiap hari mengakses mobile banking? Apakah semua orang terbiasa transaksi digital tiap minggu? Survei OJK 2023 menunjukkan hanya 49,68 persen masyarakat Indonesia memiliki literasi keuangan dasar. Artinya, lebih dari separuh rakyat negeri ini bahkan belum paham soal dasar-dasar pengelolaan keuangan digital. Lalu bagaimana mereka bisa memahami atau mempersiapkan diri menghadapi kebijakan teknokratik seperti ini?
Masalah utama dari kebijakan ini bukan pada tujuannya, tetapi pada cara dan rasa. Ia hadir secara mendadak, tanpa dialog publik, tanpa transisi edukatif, dan tanpa perlindungan hukum yang kuat bagi warga yang menjadi korban “diam”.
Negara harus sadar, langkah seperti ini dapat menumbuhkan ketakutan dan ketidakpercayaan. Bahwa hari ini rekening diblokir karena tak aktif, besok bisa jadi aktivitas digital lainnya juga dimonitor dan dibatasi dengan logika yang sama. Kita sedang menuju masa ketika privasi bukan lagi hak yang dihargai, tetapi ruang yang bisa digeledah atas nama keamanan.
Maka, editorial ini ingin menyuarakan keresahan masyarakat, sekaligus menawarkan peringatan yang lugas: hentikan pendekatan represif terhadap warga biasa, dan fokuslah pada pembenahan sistem yang adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan kepercayaan.
Pemerintah, melalui PPATK dan otoritas keuangan lainnya, perlu segera mengevaluasi kebijakan ini dengan langkah-langkah konkret:
- Notifikasi berlapis dan terverifikasi, bukan pemblokiran mendadak. Warga berhak tahu dan diberi kesempatan untuk merespons.
- Perlindungan hukum yang jelas untuk rekening pasif, agar tak sembarang saldo dianggap tak bertuan atau bisa ditindak secara sepihak.
- Pusat edukasi digital nasional, karena literasi adalah fondasi keadilan kebijakan digital.
- Saluran klarifikasi cepat dan manusiawi, agar warga tidak dipingpong ketika mencari kejelasan atas hak mereka.
- Revisi batas waktu dormansi, dari tiga bulan menjadi minimal 12 bulan—mengacu pada praktik internasional.
- Pendekatan berbasis risiko dan data forensik, bukan berdasarkan asumsi diam = salah.
Negara tidak boleh kehilangan arah moral dalam menetapkan prioritas kebijakan. Melindungi sistem keuangan adalah kewajiban, tapi melindungi warganya dari ketidakadilan prosedural adalah tanggung jawab yang lebih besar.