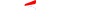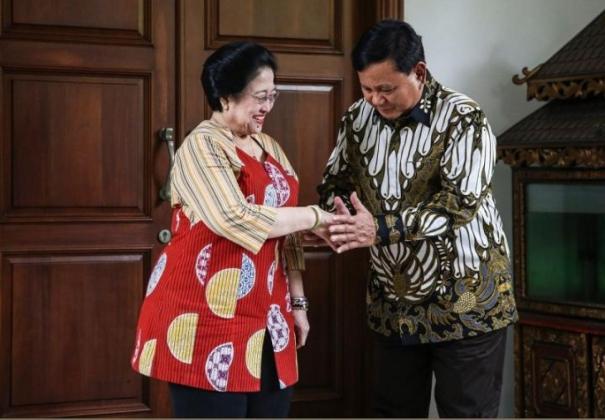JAKARTA - Model Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung bergeser menjadi demokrasi berbayar bakal berdampak buruk terhadap demokrasi di Indonesia. Efeknya, jeratan hukum bagi kepala daerah terpilih tak bisa terhindarkan. Alasannya sederhana, mereka akan menggali sumber pendapatan ”haram” untuk mengembalikan modal yang telah disalurkan.
Pernyataan ini ditegaskan Pengamat Hukum dan Tata Negara Yusdiyanto Alam, merespon pertemuan Mendagri Tito Karnavian dengan sejumlah praktisi dari 10 Univeristas dari berbagai daerah pekan lalu.
”Problematika Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 jelas berdampak pada penyelenggaraan Pilkada 2020. Karena memberikan beban berat kepada calon sampai terpilih sebagai kepala daerah akibat dari beban biaya politik yang harus ditanggung oleh kepala daerah terpilih,” papar Yusdiyanto kepada Fajar Indonesia Network (FIN) Minggu (9/2).
Beban tersebut muncul dari kebutuhan partai dan ekspektasi masyarakat. ”Hal ini menjadi aneh, Pilkada dengan biaya yang besar hanya untuk memenjarakan para kepala daerah yang baru dilantik. Hal ini tidak seimbang dengan biaya pilkada yang telah dikeluarkan. Coba saja Anda hitung. Ini catatan eksaminasi saya,” terang Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung itu.
Yusdiyanto pun memberikan contoh berulangnya Operasi Tangkap Tangan (OOT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Lampung. ”Dapat dipastikan perilaku korupsi yang serupa itu terjadi di 15 kab/kota di Lampung dan merembet ke daerah lain. Rata-rata yang ditangkap oleh KPK merupakan orang-orang terpilih dan telah melalui uji publik. Baik secara kompetensi, integritas dan berpendidikan yang lebih baik. Hal ini diduga dari efek dari modal pilkada yang besar,” terangnya.
Dari catatam yang ada isu Pilkada yang kerap muncul lebih disebabkan karena beberapa hal. Dari multi tafsir atas UU dan peraturan pilkada/pemilu, sengketa gugatan PTUN atas peraturan Pilkada sampai SDM penyelenggara yang kurang kompeten. Kompleksnya tiga hal tersebu makin diperparah dengan ketergantungan kredibilitas dan indepedensi penyelenggara, belum lagi permasalahan di perbatasan, pedalaman, kepulauan dan mobilisasi pemilih.
”Problem lain yang akan muncul, rendahnya partisipasi masyarakat, soal kampanye dari masa tenang dan pemungutan suara hingga penetapan calon terpilih. Dan pastinya publik akan disuguhkan dengan persoalan sengketa dari administrasi, pidana, mahkamah konstitusi,” terang doktor jebolan Universitas Padjajaran itu.
Persoalan akan kembali muncul dengan kosep pendistribusian logistik yang selama ini tidak terencana dan terukur termasuk terganggunya pendistribusian akibat kerawanan dan sulitnya kondisi geografis. ”Jika boleh saran, pemerintah (DPR dan Presiden. Red) harus segera merevisi Undang-Undang Pilkada. Karena secara Umum UU Pilkada tersebut hanya meletakkan pada demokrasi prosedural dengan mengabaikan demokrasi subtansial,” paparnya.
Disinggung bagaimana konsep idealnya? Yusdiyanto berharap pemerintah dan DPR dapat memasukan beberapa hal. Salah satunya bab tentang persyaratan calon. ”Pertama tentang hak politik yang tidak dicabut oleh pengadilan. Saran saya minimal 15 tahun setelah yang bersangkutan bebas dari hukuman, baru diperbolehkan,” imbuhnya.
Selanjutnya bab yang berisi tentang penyelenggara Pilkada khususnya nomenklatur kelembagaan Bawaslu. ”Menurut UU Pilkada, Bawaslu sebagai Panwas sifatnya ad-hoc. Menurut UU Pemilu, Bawaslu telah permanen. Keanggotaan, menurut UU Pilkada tiga orang, sedangkan menurut UU Pemilu tiga sampai tujug orang. Ini yang membuat rancu,” jelasnya.
Nah, yang paling mencolok, ada di Pasal 30. ”Tugas wewenang Panwas harus ditambah terkait sejak NPHD ditanda-tangani sudah mulai bekerja, termasuk memantau proses penjaringan calon yang dilakukan oleh partai politik,” urainya.
Bab selanjutnya tentang hak memilih. Yusdiyano menyarankan perlu diakomodir pemilih yang tinggal di kawasan hutan, lembaga pemasyarakatan dan penyadang disabiitas dengan perekaman data pemilih berbasis digital. ”Dan yang perlu direvisi selanjutnya adalah bab kampanye. Di dalamnya ada batasan waktu mengingat sekarang hampir delapan bulan dan sangat tidak efektif dan berlebihan, termasuk biaya kampanye calon perlu dirasionalisasi,” terangnya.
Yusdiyanto juga mengkritisi soal laporan penerimaan pengawasan sumbangan dana kampanye. Selama ini kepatuhan pelaporan cukup meningkat tetapi kebenaran rendah, terlebih dalam UU Pilkada tidak ada sanksi yang memberikan efek jera terkait sumbangan dan penggunaan dana pilkada. ”Justru penyelenggara memberikan kesempatan pada calon kepala daerah dan wakilnya untuk memberikan laporan yang tidak benar,” ungkapnya.
Untuk mengatasi hal ini perlu ia pun memberikan beberapa rekomendasi. Pertama ruang lingkup peraturan. Di dalamnya harus disertakan pelaporan dan pengawasan biaya Pilkada yang dikeluarkan paslon harus diperluas yaitu pra kampanye dan pasca kampanye (biaya saksi dan biaya sengketa). Demikian pula dengan laporan sumbangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan terakhir penyusunan mekanisme pendanaan partai yang akuntabel.
Bab partisipasi masyarakat, menurutnya juga perlu diperluas dengan melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi, ormas dan organisasi kepemudaan sebagai bentuk kerjasama dalam hal pengawasan Pilkada. Termasuk bab tentang penangan Laporan Pelanggaran Pemilihan, Bawaslu harus diposisikan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu namun diperluas yaitu Bawaslu sebagai pencegah sekaligus penindak yang tidak hanya mengedepankan prosedur hukum namun juga substansi hukum baik secara tempus delik maupun locus delik.