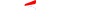JAKAARTA - Rencana Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) kini telah masuk ke DPR. RUU Omnibus Law Cipta Kerja dinilai tidak pro terhadap buruh. Sehingga suara penolakan atas RUU makin nyaring terdengar. Bahkan berbagai elemen organisasi buruh mengancam akan turun ke jalan demi menolak RUU tersebut.
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban menegaskan seluruh elemen buruh yang tergabung dalam KSBSI akan menolak RUU Omnibus Law dengan melakukan aksi unjukrasa di berbagai daerah. "Kita akan aksi turun ke jalan, mulai tanggal 2 Maret 2020. Puncaknya 11 Maret 2020, semua berpusat di kantor DPRD tingkat 1 dan 2," jelas Elly dalam konfrensi persnya di kantor KSBSI Jakarta , Rabu (19/2).
Menurutnya, setelah dilakukan pengkajian mendalam terdapat tiga alasan pokok penolakan RUU RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pertama aspek Filosofis. Sesuai amanat UUD 1945 pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D bahwa Negara memiliki tanggungjawab untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya dimana setiap warga negara berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak termasuk kelangsungan kerja dan jaminan upah untuk hidup layak.
Dalam konteks sekarang di UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ada jaminan dimana upah dilakukan review per-1 tahun yang terdapat 3 runutan sistem pengupahan. "Lalu bila sekarang RUU Cipta Kerja menghapuskan sistem tersebut maka pengelola negara tidak lagi dalam posisi menjalankan UUD 1945. Bahkan mendegradasi. Kami menilai RUU ini harus ditolak karena bertentangan dengan konstitusi tertinggi negara," tegasnya.
Kedua aspek Sosiologis. Elly menyebut sekarang ada norma membatasi praktek kerja kontrak. Dengan pembatasan sistem kontrak selama ini, dimana-mana terjadi pensiasatan. Sehingga kontrak bisa berlangsung puluhan tahun. Dengan adanya RUU ini, maka kondisinya berarti pembenaran pada praktek-praktek buruk yang ada selama ini. KSBSI sebagai Serikat buruh berjuang agar pembatasan tersebut tetap diberlakukan. Sehingga para buruh Indonesia, calon-calon para pekerja/buruh tidak terjerembab pada status kehidupan sosial yang bernama buruh kontrak. "Ini berarti cukup membahayakan bagi kehidupan masyarakat. Karena itu, kami menolaknya," ucapnya.
Yang ketiga aspek yuridis. Landasan hukum pembentukan RUU Cipta Kerja adalah UU No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang sebagaimana diubah dengan UU yang terbaru No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang. Prinsip dasarnya adalah segala aturan perundang-undangan yang diciptakan oleh negara harus melalui proses yang disebut sosialisasi pada awal pembentukan.
Pembentukan Peraturan Undang-Undang, seharusnya sudah dilakukan sosialisasi melalui proses hearing atau dengar pendapat yang diaktualisasikan melalui Naskah Akademik (NA). "Berdasarkan pandangan secara juridis apa yang dibuat dalam RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan sesungguhnya Omnibus law ini bertentangan dengan prinsip hukum yang dianut Indonesia," urainya.
Sebab, lanjut Elly, ini adalah prinsip yang dianut oleh negara sistem common law. Dari sisi yuridis tersebut, KSBSI menyarankan nilai yang ada di UUK No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan semestinya sebagai batu loncatan untuk membuat norma yang lebih baik. Bukan mendegradasi menjadi lebih buruk.
Dikatakan, KSBSI sebagai organisasi yang berdiri sejak tahun 1992 berprinsip mendukung pemerintah yang kebijakannya pro pada kehidupan masyarakat dan buruh. Sebaliknya, KSBSI akan bersikap apabila pemerintah zolim pada pekerja atau buruh. "Maka KSBSI di akan berada di depan untuk melawan," terangnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing mengatakan Omnibus Law terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja, khususnya pasal 170 ayat (1) mengalami kecelakaan akademik. Sebab sangat jelas tertuang dalam konstitusi, sebagai negara demokrasi, bahwa pembuatan dan atau perubahan UU merupakan produk DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah Pusat.
Jadi, merujuk pada konstitusi, Lembaga Kepresiden belum diberikan kewewenangan membuat dan atau mengubah UU. Selain inkonstitusional, isi ayat tersebut memberikan luasan atau keleluasaan dan kewenangan yang luar biasa kepada Pemerintah Pusat, hampir tanpa batas. "Bayangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang lebih rendah dari UU, bisa mengubah isi pasal dan atau ayat dari suatu UU. Sangat mengejutkan. Terlepas dari apa agenda di balik pembuatan narasi, rumusan tersebut dapat dikategorikan sebagai kecelakaan akademik dari aspek konstitusi dan demokrasi," jelas Emrus.(lan/fin/rh)