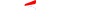Oleh: Sigit Nugroho, Redaktur fin.co.id
DAHULU , pada era 90-n ketika matahari mulai muncul menerangi pagi, teriakan bocah penjual koran familiar terdengar di telinga kita. Bukan hanya sekali saja, teriakan "korannya koran, Sinar Pagi, Kompas, Media Indonesia, koran" bisa berulang kali terdengar lewat di depan rumah.
Teriakan pagi yang membangunkan semangat itu kini sudah tak terdengar lagi di telinga kita. Jangankan tukang koran keliling, lapak penjual koran pun hampir tak nampak lagi di pinggir-pinggir jalan, di persimpangan-persimpangan, juga di sudut-sudut kota di tengah kemacetan lalu lintas.
Era digital merenggut semua itu. Mulai dari munculnya detikcom, inilah, hingga okezone dan lainnya, sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti, mulai menggeser kedigdayaan media massa seperti koran dan majalah yang di era nya, sempat menjadi kontrol sosial bagi siapapun yang berkuasa.
Kedahsyatan Majalah Tempo yang pada era Orba paling sering diberedel, seolah mulai senyap. Masih ada, namun berat untuk mengulangi kejayaan masa lalunya.
Era 2000-an, kemunculan media daring seolah menjadi suatu keniscayaan. Perkembangan gadget, dari sekedar alat komunikasi menjadi alat yang serba bisa, turut mempercepat transformasi media analog ke digital.
Kemudahan dan kecepatan informasi, menjadi keharusan ketika itu. Meski beberapa unsur mulai hilang, bahkan jika merujuk sebuah pernyataan pendiri Jawa Pos, Abah Dahlan Iskan, bahwa kasta tertinggi jurnalisme adalah jurnalistik koran, maka di era jurnalisme digital, semuanya mulai bergeser.
Baca Juga
Pakemnya jelas, seorang jurnalis bisa dianggap berkompeten ketika ia berhasil melalui ujian yang disebut Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Meskipun banyak juga jurnalis yang belum tersertifikasi namun tetap berkompeten dan memiliki segudang pengalaman.
Era digital merubah segalanya. Bahkan, modul UKW saja hanya ada sesuai materi untuk penulisan surat kabar, belum ada modul ujian untuk wartawan digital, yang mana prinsip 5W1H seolah tak perlu lagi ada di dalam satu berita.
Belum sampai para jurnalis berdamai dengan tuntutan zaman dan pergeseran ke era digital, kini lagi-lagi jurnalis harus berjibaku dengan perkembangan zaman yang terlalu pesat. Tak perlu lagi yang namanya kode etik jurnalistik, siapapun dan kapanpun, dalam situasi apapun semua orang bisa menjadi wartawan dadakan dengan platform media sosial.
Celakanya, bahkan media sosial ini lebih dipercaya ketimbang media massa mainstream yang nerlandaskan kode etik dan pedoman media siber. Tak perlu lagi yang namanya editor/redaktur, penanggung jawab konten. Siapapun, kapapun dan dimanapun, semua orang bisa memposting "berita" di sosial media masing-masing.
Indikator suksesnya tulisan wartawan dadakan itu bukan lagi visi dan misi informasi tervalidasi yang tersampaikan ke pembaca, tapi indikasi suksesnya suatu postingan adalah, viral, fyp, dan bikin heboh jagat maya.
Entah siapa yang harus dipersalahkan dengan kemajuan digital yang seperti ini. Namun, pemerintah sendiri yang menciptakan aturan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Media Terverifikasi, hingga pembentukan Dewan Pers untuk mengatur dan mengawasi media massa, justru kini merekalah yang memporakporandakan itu semua.
Influencer kini lebih dipercaya dan dibutuhkan pemerintah, ketimbang Jurnalis yang terverifikasi seperti aturan yang pemerintah buat sendiri.
Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Gading Marten, Wili Salim, hingga Atta Halilintar dan istrinya Aurel Hermansyah, bahkan Ananda Omesh dan juga Irwansyah, lebih mudah menemui Jokowi ketimbang Jurnalis berkompetensi yang menulis untuk media terverifikasi dewan pers, yang bahkan tidak mendapatkan akses untuk mendampingi Presiden dalam agenda kerja kenegaraan.